QRIS, Behavioral Economics, dan Literasi Keuangan Digital (Banjarmasin Post, Tribun Forum, 11 Februari 2020. Hlm. 6)
Oleh: Khairunnisa
Musari*
Bank Indonesia telah resmi memberlakukan Quick
Response Code Indonesia Standard (QRIS) pada 1 Januari 2020. QRIS adalah QR
code berstandar nasional yang berfungsi sebagai alat pembayaran. QRIS
adalah jawaban Bank Indonesia atas perkembangan inovasi teknologi dan maraknya kanal
pembayaran berbasis QR code.
Seiring kian beragamnya alternatif sistem
pembayaran digital, hal yang tidak boleh diabaikan oleh Bank Indonesia adalah meningkatkan
literasi keuangan digital. Berlakunya QRIS dapat menjadi momentum untuk digiatkannya
literasi keuangan digital. Literasi ini bukan sekedar agar masyarakat melek tentang
alat-alat pembayaran non tunai digital semata, tetapi juga tentang bagaimana
menghadapi era keuangan digital, termasuk mengelola dompet digital dan menjaga
keamanan data serta perangkat keuangan digital.
Melihat perkembangan peer-to-peer (P2P)
lending berbasis teknologi digital yang memakan sejumlah korban, maka sistem
pembayaran digital perlu pula mengantisipasinya. Merujuk behavioral economics,
manusia dapat tidak rasional dan kerap memasukkan unsur emosi dalam mengambil
keputusan ekonomi. Sementara, berbagai kemudahan dalam sistem keuangan digital berpeluang
mengubah atau menggeser perilaku penggunanya dengan cepat. Pertanyaannya, perilaku
tersebut akan mengarah pada perilaku seperti apa?
Behavioral Economics
Behavioral economics adalah cabang baru dalam
ilmu ekonomi yang membantu menjelaskan mengapa pengambilan keputusan ekonomi dapat
saja dikacaukan oleh bias atau kesalahan berpikir yang berulang karena terperangkap
kekeliruan atau tertipu oleh ilusi. Behavioral economics menunjukkan bahwa manusia nyatanya tidak selalu rasional dan objektif.
Dalam cabang ilmu ekonomi ini dikenal herd
behavior. Yaitu, perilaku mengambil
keputusan yang didasarkan atas perilaku
orang lain. Manusia ternyata punya kecenderungan untuk bersikap latah. Pilihan-pilihan
individu terkadang diambil karena meniru individu lain. Hal ini pula yang
mungkin dapat menjelaskan mengapa tingkat literasi keuangan di Indonesia jauh lebih
rendah daripada tingkat inklusi keuangan.
Selain itu, terdapat survivor bias. Yaitu,
perilaku mengambil keputusan yang didasarkan atas data yang tidak valid. Kesimpulan yang diambil
merujuk pada kepalsuan statistik sehingga menggeneralisirnya. Hal ini juga yang
mungkin dapat menjelaskan mengapa investasi bodong atau P2P lending ilegal
tetap dapat memikat masyarakat berdasarkan testimoni satu atau dua orang meski korban
yang berjatuhan jauh lebih banyak.
Terkait dengan sistem pembayaran digital, masyarakat
harus diedukasi untuk dapat menentukan pilihan alat pembayaran yang sesuai
dengan kebutuhan dan karakter diri. Pada prinsipnya, semua alternatif alat pembayaran
bertujuan untuk memudahkan masyarakat bertransaksi keuangan. Namun, ketidaktepatan
menentukan alat pembayaran justru dapat mempersulit diri, bahkan dapat
menimbulkan ketidakbaikan bagi penggunanya.
Penggunaan alat pembayaran digital terkadang
bukan berlatar faktor kebutuhan atau kesadaran karena pemahaman yang memadai,
melainkan herd behavior atau survivor bias sehingga cukup iming-iming
promo atau cashback membuat penggunanya langsung mengambil keputusan
bertransaksi. Jelas, berbagai kemudahan alat pembayaran digital dengan sejumlah
alternatifnya bukan tidak mengandung resiko. Salah satunya adalah kemungkinan memanfaatkan
pembiayaan berbasis teknologi digital untuk mengisi dompet digital.
Ya, aplikasi penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP)
kerap bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan dana talangan. Pembayaran
dengan menggunakan dana talangan ini sebenarnya adalah kredit. Pengguna alat
pembayaran digital yang memanfaatkan pihak ketiga ini jika tidak diikuti oleh rasionalitas
dan objektifitas dapat terjerat pada jebakan utang digital.
Behavioral economics membantu mengingatkan bahwa
pesan otoritas terhadap QRIS dan layanan non tunai digital tetap memiliki
peluang untuk diterjemahkan berbeda oleh sebagian masyarakat. Secara prinsip, transaksi
tunai dan non tunai adalah sama-sama melakukan pembayaran, hanya prakteknya
yang berbeda. Meski hal ini sangat mudah dipahami, namun secara psikologis
terdapat perbedaan ketika melakukan pembayaran secara tunai dan non tunai
berbasis digital. Hal ini yang menjadikan kebijakan tidak boleh bekerja
sendiri, tetapi juga harus bersinergi dengan para pemangku kepentingan berupaya
meningkatkan literasi.
Literasi Keuangan Digital
Kehadiran teknologi digital terus menawarkan
alternatif baru yang semakin efisien dalam transaksi pembayaran. Layanannya
cenderung lebih murah, lebih praktis, lebih transparan, mengurangi friksi
transaksi, dan konektivitas yang lebih luas. Namun, dalam konteks Indonesia, kehadiran
layanan non tunai digital bersifat opsional meski ke depan terus didorong untuk
membesar porsinya karena kebermanfaatannya yang lebih besar.
Namun, lagi-lagi behavioral economics
mengingatkan bahwa pesan layanan non tunai digital dapat diterjemahkan berbeda
oleh sebagian masyarakat. Selain dimungkinkannya terjadi pengambilan keputusan karena
herd behavior atau survivor bias, juga implikasi ketika terjadi kerugian
akan menimbulkan loss aversion sehingga mengalami keraguan atau ketakutan
untuk mengambil keputusan strategis ke depannya.
Jelas, teknologi pembayaran digital berpotensi
menimbulkan fragmentasi baru pada industri sistem pembayaran. Cara pembayaran
ini mendorong efisiensi perekonomian, memajukan usaha mikro kecil menengah (UMKM),
dan mempercepat keuangan inklusif sehingga akseptasi pembayaran non tunai nasional
yang lebih efisien akan tercapai.
Tetapi, literasi keuangan digital tidak boleh
diabaikan. Jika masyarakat paham, bijak, dan dapat mengelola alat pembayaran
digital dan keuangan digital, tentu manfaat yang akan banyak diperoleh. Namun, bila
sebaliknya yang terjadi, maka akan dengan mudah justru terjebak pada perangkap
keuangan digital. Wallahua’lam bish showab.

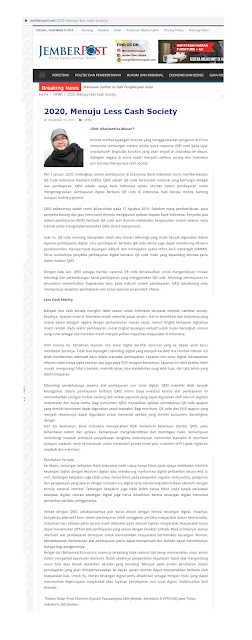

Komentar
Posting Komentar