Resiliensi Ekonomi terhadap Bencana, Sudahkah? (Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 19 Oktober 2018, Hlm. 21 & 31)
Oleh: Khairunnisa Musari*
Dear Friend
Khairunnisa
Hope
all of you are safe with the grace of Almighty Allah. We are praying for
everyone's safety and May Almighty Allah grant peace of mind to all of you.
Azhar
from Sri Lanka
Sebuah pesan masuk
via sosial media Linkedin usai gempa di Situbondo dari seorang brother di Asia Selatan. Selang beberapa
jam, saya kemudian membalas pesan tersebut untuk mengucapkan terima kasih atas
perhatiannya. Saya menduga, ia menemukan informasi bahwa Situbondo berada di
Provinsi Jawa Timur sehingga ia langsung mengirimkan pesan empati tersebut
untuk saya yang berdomisili di provinsi yang sama.
Ya, belakangan
Indonesia mengalami gempa berturut-turut. Hal ini menjadi pemberitaan global.
Sejumlah lembaga kemanusiaan internasional ikut berpartisipasi membuka donasi
untuk membantu Lombok serta Palu dan Donggala. Terakhir, gempa Situbondo.
Meskipun tidak berpotensi tsunami, gempa Situbondo terjadi dalam skala yang
cukup besar hingga bisa dirasakan di beberapa daerah. Kabar ini pun menghiasi
pemberitaan nasional.
Kerugian Ekonomi
Posisi Indonesia
yang terletak pada pertemuan tiga lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia,
Indo-Australia, dan Pasifik, menjadikan wilayah Indonesia termasuk dalam Pacific Ring of Fire yang rentan terjadi
bencana. Bencana bukan hanya gempa bumi atau tsunami, tapi juga letusan gunung
berapi, banjir lahar, amblesan, letusan
lumpur, dan tanah longsor. Dengan berbagai dampak ikutannya, segala bentuk
bencana akan berimplikasi bagi perekonomian.
World
Bank
memperkirakan dampak gempa di wilayah Palu dan Donggala menimbulkan kerusakan
secara geospasial di sektor infrastruktur, properti perumahan dan non-perumahan
yang terkena dampak tsunami mencapai USD 531 juta atau sekitar Rp 8,07 triliun.
Angka ini belum memperhitungkan kerugian atas hilangnya nyawa, kehilangan
lahan, atau gangguan terhadap ekonomi melalui pekerjaan, mata pencaharian, dan
bisnis yang hilang.
Sementara itu, Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kerugian ekonomi akibat gempa
Lombok lebih dari Rp 5,04 triliun. Berdasarkan data sementara yang dihimpun
pada 9 Agustus 2018, kerugian tersebut berasal dari sektor permukiman, infrastruktur,
ekonomi produktif, sosial budaya, serta lintas sektor. Kerusakan dan kerugian
terbesar adalah sektor permukiman sebesar Rp 3,82 triliun, disusul infrastruktur
Rp 7,5 miliar.
Bayangkan angka
ini dengan nilai pembangunan Tol Jembatan Suramadu sepanjang 5.438 meter yang menelan
anggaran Rp 4,5 triliun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, setengah dari biaya
pembangunan jembatan harus menggunakan utang. Setiap tahun, penerimaan yang
masuk ke negara dari Tol Suramadu sebesar Rp 209 miliar. Dari jumlah itu, Rp
100 miliar dipakai untuk membayar cicilan utang dan Rp 9 miliar untuk biaya
perawatan.
Ya, untuk
Indonesia, dampak bencana sangat terasa. Oleh karena itu, bisa kita bayangkan
betapa besar angka kerugian akibat tsunami di Aceh tahun 2004 yang mencapai Rp
42 triliun. Lalu, gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2006 yang
menimbulkan kerugian hingga Rp 27 triliun, dan gempa bumi Sumatra Barat tahun
2009 sebesar Rp 21,6 triliun. Untuk melakukan rehabilitasi, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) mungkin harus mengalami bleeding karena belum memiliki resiliensi ekonomi terhadap bencana.
Mengubah Paradigma
Pengalaman
menghadapi bencana memberi pelajaran mahal untuk Indonesia. Menghadapi bencana,
ternyata bukan hanya dibutuhkan pemulihan ekonomi semata. Lebih dari itu,
dibutuhkan pula revitalisasi untuk melakukan resiliensi ekonomi terhadap
bencana. Untuk itu, kebijakan APBN seyogyanya harus dibenahi agar penanggulangan
bencana menjadi bagian integral dari pembangunan.
Syukurlah, hari
ini, pemerintah tengah menyiapkan APBN untuk penanggulangan bencana. Dalam rangkaian IMF-World Bank Annual Meeting di Bali, pemerintah
menyampaikan rencana pembentukan skema pembiayaan dan asuransi risiko sebagai
upaya penanganan dampak bencana alam. Pemerintah sudah mengidentifikasi masalah
yang ada, termasuk melakukan kajian terhadap risiko fiskal atas berbagai bentuk
bencana yang implikasinya tentu berbeda-beda. Selanjutnya, hal ini seyogyanya perlu
diikuti dengan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk menentukan skema
pendanaan mitigasi atau penanggulangan bencana.
Ya, pendekatan
pasif-reaktif dengan paradigma bahwa bencana tidak bisa diperkirakan, kini
terbantahkan. Studi Yasuhide Okuyama dari Graduate
School of Social System Studies, University of Kitakyushu Jepang yang
banyak menulis tentang dampak bencana dari sisi ekonomi, menarik disimak.
Maklum, Jepang adalah negara langganan gempa. Kajian terkait bencana mendapat
perhatian besar di sana. Studi Okuyama (2004, 2007, 2009, 2016) menunjukkan bahwa
pola guncangan akibat bencana alam dapat dimodelkan sebagaimana guncangan
ekonomi lainnya pada siklus bisnis.
Kini, musim hujan sudah di depan mata. Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim
hujan di Jawa Timur akan terjadi pada bulan November. BMKG bahkan telah
memperingatkan 8 wilayah Indonesia yang paling rawan terjadi banjir bandang dan
longsor. Meski tidak masuk dalam wilayah yang diberi peringatan, tetap saja
kita harus waspada. Apalagi, terdapat titik- titik tertentu yang menjadi
langganan banjir di wilayah kita. Yang jadi pertanyaan adalah, sudahkah kita
memiliki pendekatan aktif-preventif untuk memiliki resiliensi ekonomi terhadap
bencana? Wallahua’lam bish showab.

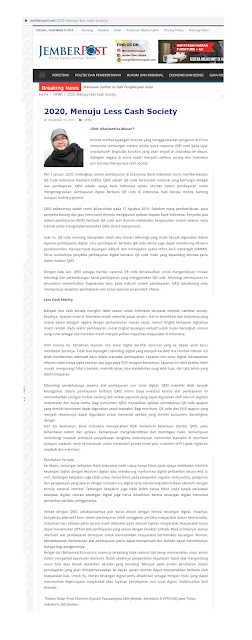

Komentar
Posting Komentar