FENOMENA BAKSO BABI & KERANG: POTRET ANOMALI EKONOMI RAKYAT (Perspektif, Radar Jember, 18 Desember 2012, Hlm. 29)
Oleh:
Khairunnisa Musari
Salah satu pemberitaan media nasional
dalam sepekan ini yang menarik perhatian adalah kasus bakso babi oplosan di Jakarta.
Bermula dari langka dan mahalnya daging sapi di ibukota selama beberapa bulan
menyebabkan pedagang bakso kelimpungan. Mereka harus mencari akal agar bahan
bakunya tetap tersedia dengan murah dan tidak perlu menjual dengan harga lebih
mahal.
Setelah tiga pedagang bakso dan satu
lokasi penggilingan bakso ditemukan memakai oplosan daging babi, hampir seluruh
pedagang bakso di wilayah Jakarta menjadi resah. Sampel bakso mengandung babi
ditemukan di semua wilayah Jakarta, baik Selatan, Timur, Utara, dan Barat.
Pedagang yang tetap mempertahankan keaslian daging sapi sebagai bahan baku baksonya
ikut terimbas. Jualannya menurun. Dalam satu waktu mereka umumnya dapat menjual
ratusan mangkok, pasca terkuaknya oplosan daging babi membuat mereka hanya
mampu menjual 10 mangkok.
Tak berbeda jauh dengan Jakarta, di Surabaya
pun pedagang bakso mengakui harga daging sapi cukup mahal meski tidak sampai
selangka di Jakarta. Untuk menyiasati, mereka mengurangi ukuran bakso atau
menambahkan jualan siomay.
Di Jember, awal Desember lalu, harga
daging sapi yang sempat mencapai Rp 85.000 per kilo mulai berangsur normal di
kisaran Rp 75.000 per kilo untuk daging sapi biasa dan Rp 78.000 per kilo untuk
daging sapi super. Penurunan ini didorong oleh menurunnya permintaan dan berkurang
jumlah sapi yang dipotong di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) akibat mahalnya harga
sapi.
Anomali ekonomi rakyat yang tercermin
dari perilaku pedagang bakso di Jakarta disebabkan oleh motif ekonomi pedagang
sebagai dampak kebijakan pemerintah. Terdesak oleh kebutuhan, mereka mencari
jalan untuk dapat bertahan hidup. Sejumlah himbauan telah dilakukan pemerintah
maupun asosiasi terkait agar masyarakat tidak resah dan tetap mau mengkonsumsi
bakso asal berhati-hati. Bagaimanapun, bakso sebagai makanan keseharian
masyarakat Indonesia merupakan tulang punggung banyak keluarga yang
menggantungkan hidupnya dari perdagangan ini.
Anomali ekonomi rakyat lain yang dapat
kita simak adalah kegiatan perdagangan kerang sebagai hasil laut dan perikanan.
Kerang hijau (Mytilus viridis atau Perna viridis), kerang darah (Anadara granosa L.), dan kerang bakau (Polymesoda bengalensis L.) adalah salah
satu jenis kerang yang paling sering dikonsumsi masyarakat. Kerang selama ini dipahami
sebagai sumber nutrisi yang baik karena kandungan mineral, protein, asam lemak
omega 3, dan lemak jenuh yang rendah.
Namun, mungkin tak banyak yang
mengetahui, layaknya penyedot debu, kerang mampu menghisap apapun yang ada di dekatnya,
termasuk menjaring racun, logam berat, dan sedimen lumpur. Sebagai kelompok mollusca, kerang yang diapit cangkang ini
tidak memiliki organ hati untuk menghancurkan benda asing. Akibatnya, semua
benda asing ditampung di dalam dagingnya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa kerang-kerangan
memiliki potensi bahaya. Kerang hidup berkelompok di dasar laut dangkal dekat
pantai, di mana sampah manusia dan buangan industri berhimpun. Konsentrasi
bakteri dan zat racun di dasar laut menyebabkan kerang mudah tercemar.
Sepuluh tahun lalu, kerang-kerangan
Indonesia ditolak oleh negara-negara Uni Eropa. Ekspor kerang terganjal oleh
adanya indikasi banyaknya racun di kerang perairan Indonesia. Sejumlah
psikiater, psikolog, dokter anak, dan orangtua yang memiliki anak autis dalam
sejumlah forum juga memberi himbauan agar kerang dihindari, terutama bagi ibu
hamil dan anak autis. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
menyatakan, kerang di Indonesia timur yang tercemar mencapai 10 hingga 20 kali
lipat dibandingkan dengan pulau Jawa.
Informasi tentang potensi bahaya
mengonsumsi kerang sudah mulai berani dinyatakan terbuka oleh Dinas Kelautan
dan Pertanian DKI Jakarta yang menghimbau agar masyarakat Jakarta tidak
mengonsumsi kerang hijau. Sebelumnya, hal ini tidak pernah diumumkan lantaran argumen
penyelamatan pariwisata. Ya, perkembangan ilmu pengetahuan yang menguak potensi
bahaya kerang sesungguhnya sudah lama diketahui oleh institusi pemerintah
terkait. Namun, tak banyak yang berani menyampaikannya kepada publik. Di Surabaya
dan Sidoarjo, justru aktivis lingkungan hiduplah yang memberikan edukasi bagi
masyarakat tentang potensi bahaya ini. Meski hal tersebut diamini oleh dinas setempat
yang menyatakan bahwa bentos menyerap polutan di tempat ia hidup sehingga
tubuhnya mengandung racun, namun mereka belum berani menyampaikan secara
terbuka.
Ekonomi Tanpa
Negara
Fenomena bakso babi oplosan dan perdagangan
kerang adalah salah satu bentuk konfirmasi tentang adanya anomali sosial
ekonomi di negeri ini. Anomali mengindikasikan adanya gangguan konstruksi
stabilitas ekonomi dalam mencapai peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.
Motif utama dibaliknya adalah dorongan kebutuhan ekonomi. Dorongan inilah yang
membuat seseorang atau sekelompok orang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan
tindakan penyimpangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Dalam hal ini, negara tanpa sadar turut
ambil bagian dalam mendistorsi daya tahan ekonomi masyarakat. Keterlibatan
negara melalui perangkat birokrasinya tidak jarang juga menjadi pemicu high cost economy yang menghambat
akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Banyak bukti empirik, pada
level kebijakan di pemerintahan daerah, negara justru melumpuhkan kekuatan
ekonomi lokal, yang kemudian diganti dengan paradigma pragmatis eksploitatif dengan
dalih peningkatan investasi atau pertumbuhan ekonomi.
Jika bakso babi oplosan dapat dinilai
sebagai ‘gangguan’ karena terkait dengan kehalalannya bagi mayoritas penduduk
muslim Indonesia, maka perdagangan kerang menjadi ‘gangguan’ karena terkait
dengan masa depan anak bangsa. Meski kerang tidak bisa dituding sebagai
penyebab utama lahirnya anak-anak autis, namun potensinya yang dapat mengganggu
kesehatan seharusnya menjadi catatan bagi pemerintah.
Jelas, dalam hal ini dibutuhkan edukasi
dan sosialisasi untuk menyampaikan informasi bagi publik. Untuk bersiasat atas
mahalnya harga daging sapi, pakar kuliner dan gizi tentu dapat menawarkan
sejumlah opsi ketimbang daging celeng sebagai campuran bakso. Jika pemerintah
tidak dapat menjamin tidak adanya kontaminasi bagi hasil laut dan perikanan,
maka pemerintah seyogyanya mencarikan jalan keluar bagi pembudidaya untuk
beralih profesi. Kalaupun ada upaya lain untuk mereduksinya, misalnya dengan
melakukan purifikasi, maka opsi ini pun dapat dipilih meski menuntut kerja berat
dan biaya besar untuk pembelajaran masyarakat.
Apapun itu, tidak mungkin dibiarkan
ekonomi rakyat berjalan tanpa negara meski pada prakteknya justru hal itu
banyak terjadi. Tidak jarang, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak mendesak
rakyat kecil berada pada posisi sebagai oknum atau korban. Perdagangan bakso
babi oplosan dan kerang hanyalah studi kasus dari potret anomali ekonomi rakyat
di mana tidak terjadi sinergi komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antara pemerintah
dan elemen masyarakat. Tapi bagi mereka yang berpegang pada ilmu pengetahuan
dan meyakini bahwa ilmu ekonomi sebagai ilmu moral, maka yakinlah bahwa ilmu
itu netral. Ilmu menjadi tidak netral ketika dimasuki oleh kepentingan. Namun,
ilmuwan tidak boleh netral. Ilmuwan harus punya nurani dan berpihak pada
kebenaran ilmiah yang diyakini kebaikannya bagi ummat. Wallahua’lam bish showab.

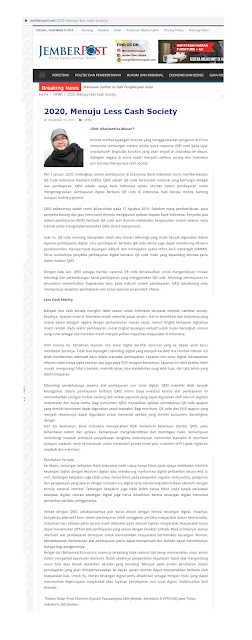

Komentar
Posting Komentar