SWASEMBADA KEDELAI, MUNGKINKAH? (Radar Jember, 10 September 2012)
Oleh: Khairunnisa Musari
“Kedelai langka, eh petani disuruh tanam kedelai. Kalau harga rendah
dan produktifitas kecil, masa kita para petani mau nanam. Mending tanam
palawija yang lain. Kalau mau nekan, tinggal mau beli dengan harga mahal
kagak? Wani piro? Saran saya, mending gak usah makan tempe dan tahu, ganti saja
dengan kangkung, simbukan, daun bluntas, lele, wader, dan belut. Murah. Tidak
repot!”
Itulah secuplik status
Fesbuk dari Pak Soegito asal Puger, Jember Selatan. Pasca pemberitaan mogok
produksi tahu tempe di ibukota beberapa waktu lalu, yang diikuti dengan pencanangan
pemerintah untuk berswasembada kedelai tahun 2014, Pak Soegito menyampaikan
uneg-unegnya di status Fesbuk.
Pak Soegito mungkin
bukan petani sejati. Usahanya lebih banyak berkonsentrasi pada bisnis ayam
pelung. Tetapi, keluarga besarnya menanam kol dan jagung. Bagi Pak Soegito dan
keluarga, menanam kedelai tidak ada menariknya. Menanam jagung terbukti jauh
lebih menguntungkan. Meski biaya produksi kedelai lebih rendah daripada jagung,
tetapi hasilnya sedikit. Dalam lahan 1 hektar yang sama, produksi jagung dapat
mencapai 3-4 kali lipat dari kedelai. Meski harga jual kedelai lebih tinggi
daripada jagung, tetapi biasanya harga kedelai jatuh saat panen. Belum lagi
tenaga yang harus dikeluarkan untuk menjemur, menumpuk, dan menjemur lagi
sampai kira-kira seminggu baru bisa didores dan dijual.
“Dulu
tuh Mbak, yang namanya jagung itu besarnya cuma sebesar jempol kaki. Jadi,
hasilnya di bawah kedelai. Lha, kalau sekarang jagungnya sak lengan-lengan dan hasilnya berlipat-lipat!
Di Amerika, kan juga begitu kejadiannya. Banyak petani kedelai yang pindah ke
jagung karena hasilnya lebih besar. Makanya, supply turun dan demand tetap, so mau enggak mau harga kedelai jadi naik.
Sekarang tinggal kita saja yang menyiasati tempe diganti dengan perkedel jagung
atau iwak peyek!” papar Pak Soegito kepada saya.
Saya tidak menampik pendapat Pak Soegito
karena jawaban senada juga ditemukan dari pihak lain yang banyak berkecimpung
di sektor pertanian. Mereka lebih tertarik menanam jagung daripada menanam
kedelai. Meskipun harga kedelai saat ini mencapai Rp 8 ribu per kilogram, tetapi petani
lebih tertarik menanam jagung. Beberapa alasan yang dikemukakan diantaranya
karena sulitnya mendapat benih kedelai, sulitnya memenuhi kebutuhan air, perawatannya
yang harus intensif, harganya yang tak stabil, dan tidak ada jaminan pasar.
Kedelai
dan Perut Rakyat
Pemerintah
sejauh ini menyatakan optimismenya bahwa Indonesia dapat meningkatkan produksi
kedelai dalam negeri guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar 2,6 juta ton
kedelai. Untuk itu, pemerintah akan menambah luas areal tanam. Luas areal tanam
kedelai saat ini sekitar 600 ribu hektar dengan kapasitas produksi 1,5 juta
ton. Direncanakan akan ada penambahan lahan seluas 400 ribu hektar lagi dengan
kemampuan produksi 2,5 ton per hektar.
Produk turunan utama dari kedelai di
Indonesia memang adalah tahu tempe, porsinya mencapai 85%. Yang menjadi
persoalan, makanan yang menguasai perut orang banyak ini bersumber utama dari
impor hingga mencapai 70%. Pada titik inilah kedelai impor berhasil menjadi
perangkap bagi Indonesia. Pada situasi ini, pemerintah seharusnya melakukan
intervensi. Intervensi tidak melulu diartikan campur tangan terhadap harga
pasar, tetapi yang utama adalah mengkondisikan agar pasar tidak mengalahkan
daulat rakyat kebanyakan. Jika Indonesia tak mampu menyediakan apa yang menjadi
kebutuhan rakyat banyak, maka seharusnya diupayakan agar rakyat tidak
bergantung padanya. Perlu dicarikan jalan keluar agar ada substitusi yang dapat
memenuhinya.
Jika disimak, kedelai lokal sesungguhnya
juga memiliki keunggulan atas kedelai impor. Pada kedelai lokal, rendemennya
lebih tinggi dan tidak berasal dari benih transgenik sehingga minim resiko
terhadap kesehatan. Sejumlah peneliti pemulia kedelai juga menyatakan kandungan
gizi kedelai lokal lebih unggul ketimbang impor. Sejumlah pihak bahkan ada yang
menduga bahwa kedelai impor sarat ampas dengan sari pati yang rendah. Tak
sedikit yang mengatakan bahwa tahu tempe yang berasal dari kedelai lokal ternyata
juga jauh lebih maknyusss.
Namun demikian, kedelai lokal punya
masalah dalam hal fisik. Selain ukurannya yang kecil, kulit ari kacang sulit
terkelupas saat proses pencucian sehingga proses peragiannya lebih lama. Setelah
berbentuk tempe, proses pengukusannya agar menjadi empuk membutuhkan waktu
lama. Dalam hal produksi, umur tanaman kedelai lokal lebih singkat 2,5-3 bulan
daripada impor yang mencapai 5-6 bulan. Namun, kapasitas produksi kedelai impor
lebih besar. Selain bijinya yang lebih besar, kemampuan produksi dapat mencapai
2 kali lipat dari kedelai lokal per hektarnya. Ditambah lagi dengan kurang
memadainya prasarana dan sarana industri, seperti minimnya penyediaan
pembenihan, terbatasnya areal tanam, dan mekanisasi usaha tani yang bersifat
tradisional, menyebabkan produksi kedelai secara nasional menjadi tak memikat.
Kedelai dan
Jember
Dalam kunjungan Menteri Perdagangan
pertengahan Agustus lalu ke Desa Curahlele Kidul, Jember, saya baru mengetahui
bahwa setengah dari produksi kedelai nasional berasal dari Jember. Subhanallah! Kemampuan produksi kedelai
Jember diberitakan mencapai 2-2,5 ton per hektar. Pak Menteri mengharapkan agar
bibit yang digunakan di Jember ini dapat disebarkan ke daerah lain.
Bisa jadi, potensi kedelai Jember ini
pula yang menjadi salah satu alasan bagi Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten
Jember mendirikan Gabungan Koperasi Petani (Gakoptan) untuk turut serta mengembangkan
komoditas kedelai sebagai salah satu produk pertanian andalan Jember. Gakoptan
yang awalnya diorientasikan untuk pengembangan kakao sebagai tanaman rakyat
unggulan, dalam perkembangannya ternyata juga menjadikan kedelai sebagai bisnis
komplemen.
Dengan keterbatasan sumber daya untuk
menginisiasi, Dinas Koperasi mengajak koperasi-koperasi petani untuk tanggung
renteng memodali usaha ini. Modal yang saya maksud di sini bukan hanya
finansial, tetapi juga dalam menyediakan lahan dan pelaku usaha. Tentu saja hal
tersebut patut diapresiasi.
Namun demikian, realita menunjukkan
adanya kendala pengembangan kakao dan kedelai jika tidak disertai dengan penambahan
lahan baru. Jika harus menggunakan lahan produktif yang lama, petani harus
benar-benar diyakinkan untuk bersedia menanam secara khusus dan pemerintah
daerah harus dapat menjamin pasar serta tidak mengurangi tanaman komoditas lain
yang lebih menguasai hajat perut orang banyak. Jalan tengah yang paling mungkin
dilakukan adalah menerapkan kebijakan tumpang sari atau pemanfaatan lahan tak
produktif. Dalam hal ini, kita tentu mengharapkan Gakoptan dapat menjadi pionir
dalam upaya menjamin pasar dan pemerintah pusat maupun daerah dapat memberi
insentif berupa harga pokok penjualan maupun harga pembelian pemerintah yang menguntungkan
petani, perajin, maupun konsumen.
Terakhir, saya ingin mengutip pernyataan
Bung Hatta dalam pidato di perayaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun
1954. “...Pada dasarnya kita harus
menghasilkan barang-barang keperluan hidup bangsa yang bahannya terdapat di
tanah air sendiri....”. Sebuah Hadits menyatakan, ‘padang rumput, air, dan api’ adalah 3 elemen substansi kehidupan
orang banyak. Tak pelak lagi, siapa yang menguasainya, maka seharusnya dialah
yang menguasai kehidupan. Sayang, kebanyakan dari kita baru menyadari ketika krisis
telah terjadi. Pangan, air, dan energi menjadi masalah nyata di dunia. Lagi-lagi,
respon yang muncul di negeri ini biasanya bersifat jangka pendek. Jika tak disertai
komit dan ke-istiqomah-an, jangan
heran jika swasembada kedelai 2014 hanya menjadi mimpi. Wallahua’lam bish showab.

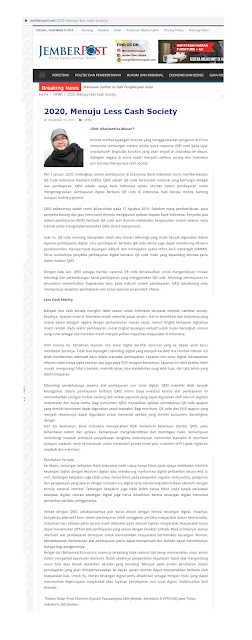

rajin menulis dimana-mana mbak :)
BalasHapusSalam dari ladang,
http://pencangkul.blogspot.com