REFORMASI AGRARIA (Radar Jember, Perspektif, 17 Juli 2010)

Oleh: Khairunnisa Musari
Jujur saja, saya agak khawatir menulis topik ini pada Perspektif. Tapi, rasanya penting buat saya untuk membahasnya. Bukan untuk memihak. Tapi untuk mengajak semua pihak terkait berembuk agar persoalan yang ada menjadi berujung dan membawa kebaikan bersama. Terlebih lagi, dengan periode baru dari Pemkab Jember yang diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam mengemban amanah masyarakat.
Mungkin masih ada yang ingat tentang sengketa tanah perkebunan kopi Ketajek seluas 17 hektar antara masyarakat dengan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP), badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemkab Jember? Konon, tanah sengketa tersebut pada mulanya adalah tanah hasil babatan masyarakat pada tahun 1942. Para petani kemudian mengajukan surat permohonan kepemilikan kepada pemerintah. Pada tahun 1964, Kementerian Agraria mengabulkan permohonan tersebut. Namun, 10 tahun kemudian masyarakat pemilik tanah tersebut diusir dari tanahnya karena dijadikan perkebunan oleh PDP.
Pemkab Jember menyatakan, alat bukti kepemilikan tanah yang dimiliki para petani sudah tak berlaku lagi. Para petani pemilik tanah tersebut dianggap telah merebut dan menduduki tanah perkebunan Ketajek milik PDP.
Jember memang bukan satu-satunya daerah yang mempunyai masalah sengketa tanah antara masyarakat melawan perusahaan daerah, perusahaan negara, pemerintah atau TNI. Sengketa sejenis ini terjadi merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Menurut catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN), data sengketa agraria hingga tahun 2006 terdiri dari 1.423 kasus, konflik terdiri dari 322 kasus, dan perkara terdiri dari 1.065 kasus. Totalnya menjadi 2.810 kasus. Setelah diverifikasi kembali pada tahun 2007, jumlah sengketa menjadi 4.581 kasus, konflik 858 kasus, dan perkara 2.052 kasus. Totalnya menjadi 7.491 kasus.
Di Jawa Timur, berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sengketa agraria hingga tahun 2006 meliputi 172 kasus. Luas lahan sengketa mencapai ± 397.684,09 hektar. Jumlah korban dalam sengketa mencapai ± 363.402 KK atau 1.609.871 jiwa. Cakupan sengketa mencapai 259 desa di 136 kecamatan dan 31 kota/kabupaten. Lawan sengketa terdiri dari 70 pihak pemerintah, 9 militer, 32 perusahaan negara, dan 62 perusahaan swasta.
Dari sisi hukum, kasus sengketa tanah Ketajek memang memiliki keanehan. Pasalnya, tanah yang sudah diberikan haknya kepada masyarakat petani yang memohon kemudian diberikan pula oleh BPN kepada PDP.
Saya mencoba menanyakan solusi hukum bagi persoalan ini kepada seorang aktivis Lembaga Hukum dan HAM Keadilan Indonesia (LHKI). Disampaikannya, apabila inisiatif penyelesaian administrasi negara tersebut tidak dilakukan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, maka para petani korban sengketa tanah dengan perusahaan perkebunan dan lain-lain yang membuat tanah sengketa menjadi tanah perkebunan, dapat mengajukan uji materiil UU Perkebunan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini mengingat UU tersebut dalam praktiknya kerap dijadikan alat kriminalisasi sehingga melanggar prinsip HAM dan model ekonomi sosial dalam konstitusi.
Disarankannya pula, rakyat petani korban dapat mengadukan persoalan tersebut kepada Komnas HAM agar dilakukan investigasi mendalam berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM berupa keputusan perampasan hak milik atas tanah para petani, serta tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum yang melakukan kriminalisasi, serta siapa saja pihak yang terlibat.
Tidak hanya itu, rakyat petani korban sebenarnya juga bisa mengajukan upaya hukum berupa gugatan perdata kepada perusahaan perkebunan pemegang hak guna-usaha (HGU) tanah sengketa, BPN, serta pemerintah daerah berkaitan dengan cacatnya proses pengumpulan data fisik dan yuridis dalam penerbitan HGU tersebut. Namun, tentu saja upaya ini dapat ditempuh jika hasil investigasi Komnas HAM menemukan fakta cacat yuridis tersebut dan tidak ada keputusan pemerintah mengenai pemenuhan hak rakyat petani yang menjadi korban.
Dari sisi ekonomi, pemerintah pusat nyatanya telah berkalkulasi bahwa kebijakan pertanahan yang terjadi saat ini telah merugikan negara dan rakyat begitu besar. Menurut catatan BPN, berbagai persoalan tersebut telah menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Secara nasional, luas tanah produktif obyek sengketa yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal seluas 6.078.860.000 m2. Nilai tanah yang menjadi obyek sengketa ini jika dihitung dengan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah terendah yang setara Rp 15.000, maka kerugian negara telah mencapai Rp 91,1829 triliun.
Hal lain yang patut dicermati dari berbagai kasus sengketa tanah sejenis ini adalah adanya dalih bahwa penggunaan lahan-lahan sengketa untuk perkebunan adalah dalam rangka memberikan sumber pendapatan negara atau daerah. Argumen ini sepatutnya tak layak dikemukakan lantaran negara seyogyanya tidak bertindak sebagai korporat. Negara Indonesia bukanlah korporatokrasi. Negara Indonesia secara konstitusional adalah negara yang menganut paham sosio-ekonomi.
Tidak bisa dipungkiri, keadaan yang terjadi menunjukkan bahwa pada umumnya perusahaan perkebunan berdiri di atas perlawanan masyarakat. Semua ini menjadi benih yang berpotensi bersemai menjadi konflik sosial. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, mungkin salah satunya dengan mendorong para wakil rakyat yang berada di Senayan untuk meminta pemerintah menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM agar segera membentuk Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA). Wallahu a’lam bish showab.
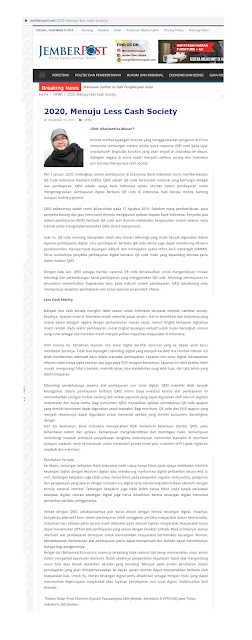

Komentar
Posting Komentar