OPINI NEWS HARIAN SINDO & KOLOM EKONOMI WWW.OKEZONE.COM, 19 JUNI 2008
TENDENSI LIBERALISASI (MIGAS)
Oleh: Khairunnisa Musari (Mahasiswa S3 Program Studi Ekonomi Islam Unair dan Peneliti INSEF)
”…politik terletak di muka, tetapi orang politik yang tidak mengetahui ekonomi tidak akan berhasil dalam menentukan tujuan tepat bagi politik perekonomian….Politik perekonomian haruslah diciptakan ahli politik yang tahu ekonomi….” (Moh Hatta,1960)
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menyisakan persoalan yang belum tertuntaskan. Kini, bayang-bayang kenaikan harga BBM jilid II sudah mengemuka. Perdebatan kembali memanas. Ada hipotesis, kenaikan harga BBM sesungguhnya bukanlah persoalan menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bukan pula persoalan dampak kenaikan harga minyak dunia. Apalagi, bukan pula persoalan banyak orang kaya yang menggunakan hak orang miskin. Melainkan persoalan liberalisasi minyak dan gas (migas) di Indonesia!
Jika merunut ke belakang, tahun 2003 merupakan tonggak hadirnya liberalisasi migas, terutama industri hilir, di Indonesia. Liberalisasi ini membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas yang selama ini dikuasai Pertamina.
Terdengar kabar, World Bank menulis surat kepada pemerintah agar para pemain baru diberi akses terhadap fasilitas produksi dan distribusi milik Pertamina. Jika tidak, para pemain baru tidak akan kuat bersaing dengan Pertamina yang sudah memiliki fasilitas lengkap.
Selanjutnya, disusunlah Pedoman Wilayah Distribusi Niaga yang mengatur distribusi migas swasta sebagai antisipasi jika Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang mendistribusikan BBM. Pada akhir 2005, Pertamina melepas kewajiban mengemban tugas pemerintah dalam pengadaan BBM domestik.
Pelepasan kewajiban ini dimaksudkan agar pemain mana saja bisa masuk untuk mengadakan dan memasarkan BBM ke pasar dalam negeri. Tidak bisa dimungkiri, kebutuhan BBM yang terus meningkat dan peluang pasar domestik yang begitu besar memberi daya tarik bagi pemain asing untuk masuk ke Indonesia.
Jika pemerintah terus memberi subsidi, iklim yang tercipta tidak bisa merangsang investor untuk berbisnis di sektor hilir. Karenanya, diaturlah mekanisme penyaluran subsidi BBM yang mengubah subsidi produk menjadi subsidi orang yang membutuhkan. Secara bertahap, pemerintah melakukan reducing subsidy yang nantinya berujung pada subsidy-removal.
Hegemoni Neoliberalisme
Hegemoni neoliberalisme yang dianut pengambil kebijakan negeri inilah yang mungkin dapat menjelaskan mengapa subsidi BBM dikurangi di tengah-tengah perekonomian sulit. Argumennya,subsidi membebani negara dan subsidi membuat rakyat tidak mandiri. Kurikulum ekonomi yang dianut kebanyakan perguruan tinggi pun sebenarnya banyak menggunakan mainstream ini. Pantaslah, banyak ekonom akademisi yang menyatakan bahwa subsidi secara konseptual adalah sebuah distorsi yang akan mendistorsi mekanisme pasar. Kesalahan kebanyakan dari kita adalah membela paradigma. Paradigma yang merupakan ciptaan manusia kerap dijadikan parameter kebenaran. Padahal, jika kita renungkan, paradigma tersebut ada yang berbenturan dengan nurani. Jika ini yang terjadi, seharusnya nuranilah yang dibela dan paradigma itu diperbaiki.
Terkait dengan tudingan bahwa subsidi merupakan beban negara, seharusnya hal itu perlu dicermati. Sesungguhnya, subsidi merupakan wujud tanggung jawab negara kepada warga negara. Jelas, negara memiliki tanggung jawab terbesar dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warganya. Sumber energi merupakan salah satu sumber daya di mana rakyat berserikat di dalamnya dan menjadikan negara sebagai pengelolanya.
Sayang, banyak dari kita yang mengagungkan pemikiran Barat dan menjadikannya kebenaran. Ditambah dengan masuknya kita dalam debt-trap dan culture-trap, bangsa ini pun menjadi semakin patuh mengiyakan kemauan pihak asing. Mereka tahu persis potensi besar bangsa ini, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, yang tidak bisa tertutupi oleh sejumlah kendala yang ada. Karenanya, Indonesia dipandang strategis untuk melakukan investasi, tepatnya lagi untuk menjadi pasar bagi mereka. Tiadanya kepercayaan diri dan kemandirian membuat kita membiarkan ”pembangunan di Indonesia” dan bukan ”pembangunan Indonesia”.
Politik Ekonomi
Dalam hal ini, politik ekonomi perlu dikedepankan.Bicara ekonomi, akan sulit jika tidak pula bicara politik. Pembangunan ekonomi sesungguhnya misi politik. Kerap persoalan ekonomi muncul dan terselesaikan bukan karena kebijakan ekonomi, melainkan kebijakan politik. Debt-trap dan culture-trap yang terjadi di Indonesia pun tidak lepas dari faktor politik.
Lebih jauh, politik ekonomi ternyata tidaklah cukup. Dibutuhkan politik ekonomi yang memahami bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu moral dan ilmu politik adalah alat perjuangan. Dibutuhkan politik ekonomi yang mampu mentransformasikan paradigma pemerintah selama ini yang membela liberalisasi sebagai wujud kemajuan peradaban menjadi paradigma yang berkeadilan. Ke depan, tentu semua sepakat bahwa subsidi harus dihilangkan.
Namun, dihilangkannya subsidi bukan karena rekayasa pihak-pihak tertentu, melainkan karena memang sudah tidak ada lagi warga yang membutuhkan subsidi. Itu berarti rakyat Indonesia sudah mandiri dan mampu berdaya dalam ekonominya. Untuk saat ini, jelas hal tersebut belum bisa terwujud. Sebab, rakyat di sekitar garis kemiskinan masih sangat besar. Intervensi negara dibutuhkan. Jelas, sangat urgen saat ini untuk menghadirkan politik ekonomi yang membela nurani, bukan membela paradigma. (*)
Oleh: Khairunnisa Musari (Mahasiswa S3 Program Studi Ekonomi Islam Unair dan Peneliti INSEF)
”…politik terletak di muka, tetapi orang politik yang tidak mengetahui ekonomi tidak akan berhasil dalam menentukan tujuan tepat bagi politik perekonomian….Politik perekonomian haruslah diciptakan ahli politik yang tahu ekonomi….” (Moh Hatta,1960)
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menyisakan persoalan yang belum tertuntaskan. Kini, bayang-bayang kenaikan harga BBM jilid II sudah mengemuka. Perdebatan kembali memanas. Ada hipotesis, kenaikan harga BBM sesungguhnya bukanlah persoalan menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bukan pula persoalan dampak kenaikan harga minyak dunia. Apalagi, bukan pula persoalan banyak orang kaya yang menggunakan hak orang miskin. Melainkan persoalan liberalisasi minyak dan gas (migas) di Indonesia!
Jika merunut ke belakang, tahun 2003 merupakan tonggak hadirnya liberalisasi migas, terutama industri hilir, di Indonesia. Liberalisasi ini membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas yang selama ini dikuasai Pertamina.
Terdengar kabar, World Bank menulis surat kepada pemerintah agar para pemain baru diberi akses terhadap fasilitas produksi dan distribusi milik Pertamina. Jika tidak, para pemain baru tidak akan kuat bersaing dengan Pertamina yang sudah memiliki fasilitas lengkap.
Selanjutnya, disusunlah Pedoman Wilayah Distribusi Niaga yang mengatur distribusi migas swasta sebagai antisipasi jika Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang mendistribusikan BBM. Pada akhir 2005, Pertamina melepas kewajiban mengemban tugas pemerintah dalam pengadaan BBM domestik.
Pelepasan kewajiban ini dimaksudkan agar pemain mana saja bisa masuk untuk mengadakan dan memasarkan BBM ke pasar dalam negeri. Tidak bisa dimungkiri, kebutuhan BBM yang terus meningkat dan peluang pasar domestik yang begitu besar memberi daya tarik bagi pemain asing untuk masuk ke Indonesia.
Jika pemerintah terus memberi subsidi, iklim yang tercipta tidak bisa merangsang investor untuk berbisnis di sektor hilir. Karenanya, diaturlah mekanisme penyaluran subsidi BBM yang mengubah subsidi produk menjadi subsidi orang yang membutuhkan. Secara bertahap, pemerintah melakukan reducing subsidy yang nantinya berujung pada subsidy-removal.
Hegemoni Neoliberalisme
Hegemoni neoliberalisme yang dianut pengambil kebijakan negeri inilah yang mungkin dapat menjelaskan mengapa subsidi BBM dikurangi di tengah-tengah perekonomian sulit. Argumennya,subsidi membebani negara dan subsidi membuat rakyat tidak mandiri. Kurikulum ekonomi yang dianut kebanyakan perguruan tinggi pun sebenarnya banyak menggunakan mainstream ini. Pantaslah, banyak ekonom akademisi yang menyatakan bahwa subsidi secara konseptual adalah sebuah distorsi yang akan mendistorsi mekanisme pasar. Kesalahan kebanyakan dari kita adalah membela paradigma. Paradigma yang merupakan ciptaan manusia kerap dijadikan parameter kebenaran. Padahal, jika kita renungkan, paradigma tersebut ada yang berbenturan dengan nurani. Jika ini yang terjadi, seharusnya nuranilah yang dibela dan paradigma itu diperbaiki.
Terkait dengan tudingan bahwa subsidi merupakan beban negara, seharusnya hal itu perlu dicermati. Sesungguhnya, subsidi merupakan wujud tanggung jawab negara kepada warga negara. Jelas, negara memiliki tanggung jawab terbesar dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warganya. Sumber energi merupakan salah satu sumber daya di mana rakyat berserikat di dalamnya dan menjadikan negara sebagai pengelolanya.
Sayang, banyak dari kita yang mengagungkan pemikiran Barat dan menjadikannya kebenaran. Ditambah dengan masuknya kita dalam debt-trap dan culture-trap, bangsa ini pun menjadi semakin patuh mengiyakan kemauan pihak asing. Mereka tahu persis potensi besar bangsa ini, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, yang tidak bisa tertutupi oleh sejumlah kendala yang ada. Karenanya, Indonesia dipandang strategis untuk melakukan investasi, tepatnya lagi untuk menjadi pasar bagi mereka. Tiadanya kepercayaan diri dan kemandirian membuat kita membiarkan ”pembangunan di Indonesia” dan bukan ”pembangunan Indonesia”.
Politik Ekonomi
Dalam hal ini, politik ekonomi perlu dikedepankan.Bicara ekonomi, akan sulit jika tidak pula bicara politik. Pembangunan ekonomi sesungguhnya misi politik. Kerap persoalan ekonomi muncul dan terselesaikan bukan karena kebijakan ekonomi, melainkan kebijakan politik. Debt-trap dan culture-trap yang terjadi di Indonesia pun tidak lepas dari faktor politik.
Lebih jauh, politik ekonomi ternyata tidaklah cukup. Dibutuhkan politik ekonomi yang memahami bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu moral dan ilmu politik adalah alat perjuangan. Dibutuhkan politik ekonomi yang mampu mentransformasikan paradigma pemerintah selama ini yang membela liberalisasi sebagai wujud kemajuan peradaban menjadi paradigma yang berkeadilan. Ke depan, tentu semua sepakat bahwa subsidi harus dihilangkan.
Namun, dihilangkannya subsidi bukan karena rekayasa pihak-pihak tertentu, melainkan karena memang sudah tidak ada lagi warga yang membutuhkan subsidi. Itu berarti rakyat Indonesia sudah mandiri dan mampu berdaya dalam ekonominya. Untuk saat ini, jelas hal tersebut belum bisa terwujud. Sebab, rakyat di sekitar garis kemiskinan masih sangat besar. Intervensi negara dibutuhkan. Jelas, sangat urgen saat ini untuk menghadirkan politik ekonomi yang membela nurani, bukan membela paradigma. (*)
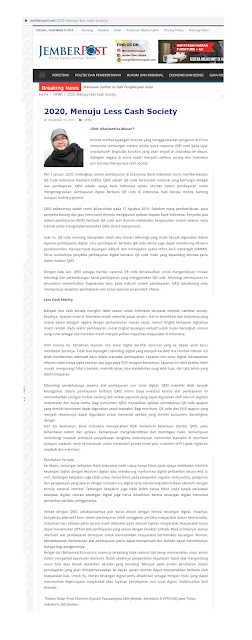

Bener Bu Iis, rasanya subsidi itu memang masih perlu sampai angka garis kemiskinan di bawah 10%. Cuma yang jadi masalah, alokasi APBN apa yang pas untuk penggantian subsidi tersebut.
BalasHapusMenurutku, pembelanjaan rutin pemerintah yang sebenarnya patut untuk dipangkas, misalnya gaji PNS. Tapi mau gimana lagi, lha wong PNS gajinya ditambah aja masih tetap buruk kinerjanya, apalagi dipangkas. Punishment dan rewards di kalangan PNS nggak jelas blas!.